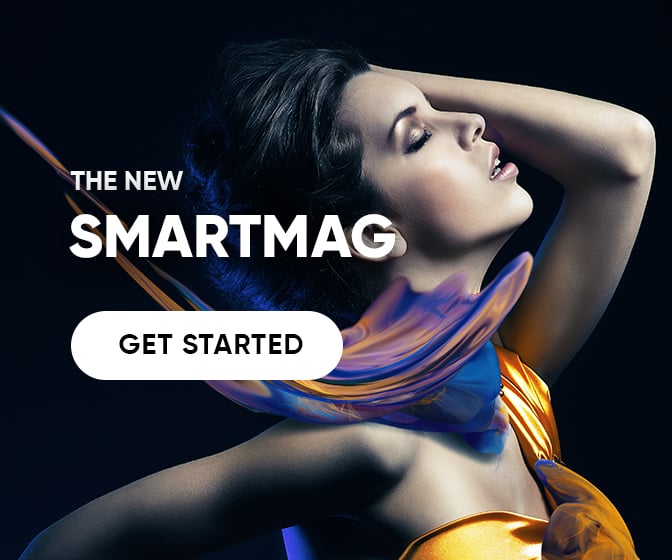Oleh Barman Wahidatan Anajar, S.Sos., Koordinator Indonesia Zakat Watch
Dalam beberapa hari ke depan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dua permohonan diajukan: perkara 54/PUU-XXIII/2025 oleh Kiai Jazir Jogokaryan bersama Indonesia Zakat Watch, dan perkara 97/PUU-XXII/2024 oleh Forum Zakat, Dompet Dhuafa, serta Arif Rahmadi Haryono. Persoalan ini bukan sekadar teknis hukum, melainkan penentu arah tata kelola zakat di Indonesia. Putusan MK akan menjawab: apakah zakat tetap berada dalam sistem yang sentralistik dan minim partisipasi, atau dibuka menuju tata kelola yang adil, transparan, dan partisipatif.
Problem UU Zakat 2011
Sejak disahkan, UU 23/2011 menyisakan persoalan serius. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ditempatkan sebagai lembaga dominan dengan kewenangan regulasi, koordinasi, hingga pengawasan. LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang lahir dari masyarakat sipil justru diposisikan subordinat dan bergantung penuh pada rekomendasi maupun regulasi BAZNAS. Sejumlah aturan turunan, seperti Perbaznas No. 1/2018, No. 3/2018, dan No. 3/2019, menunjukkan betapa kuatnya peran BAZNAS, bahkan pada ranah yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah (Kemenag).
Model ini menutup ruang partisipasi publik, membatasi inovasi, dan berpotensi menciptakan monopoli kelembagaan. Padahal zakat adalah ibadah sosial yang secara historis tumbuh dari, oleh, dan untuk umat. Ketika pengelolaan terlalu terpusat, risiko penyalahgunaan meningkat. Kasus penyalahgunaan zakat dan hibah di beberapa daerah menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan. Maka, JR ini hadir sebagai upaya meluruskan arah kebijakan agar zakat kembali ke prinsip partisipasi dan akuntabilitas.
Hak Konstitusional Umat
JR terhadap UU 23/2011 bukan upaya melemahkan negara, melainkan penguatan amanat konstitusi. Pasal 28E UUD 1945 menjamin kebebasan beragama dan berserikat, sementara Pasal 29 menjamin kemerdekaan beribadah. Dalam konteks zakat, umat berhak mengelola zakat secara mandiri dan partisipatif, bukan semata diserahkan kepada satu lembaga negara.
Pasal 34 UUD 1945 pun menegaskan kewajiban negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dengan demikian, tata kelola zakat yang bersih dan transparan merupakan pengejawantahan langsung dari amanat keadilan sosial. Jika zakat dipusatkan tanpa mekanisme kontrol publik, potensi penyimpangan akan semakin besar dan mandat konstitusi terabaikan.
Baik dalam permohonan JR 54 maupun 97, tidak ada keinginan menghapus peran pemerintah. Yang diperjuangkan adalah pemisahan peran: pemerintah menjalankan fungsi regulasi, sementara lembaga masyarakat diberi ruang beroperasi secara independen. Usulan bahkan mendorong agar regulator dikembalikan sepenuhnya ke Kementerian Agama, bukan BAZNAS.
Momentum dengan Agenda Nasional
Menariknya, arah judicial review ini sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah. RPJMN 2025–2029 yang diatur melalui Perpres 12/2025 menekankan perlunya reformasi tata kelola dana sosial-keagamaan, termasuk zakat, agar lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif.
Instruksi Presiden No. 8/2025 menegaskan mandat kepada Kementerian Agama untuk mengoptimalkan penghimpunan dan pendistribusian zakat, bukan sekadar mengejar angka, tetapi memastikan zakat mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Artinya, perjuangan JR ini justru sejalan dengan visi pemerintah.
Publik perlu memahami bahwa JR bukanlah gerakan tandingan terhadap negara, melainkan penguatan arah kebijakan yang sudah digariskan dalam RPJMN dan Inpres. Dengan putusan MK yang tepat, zakat bisa menjadi instrumen pembangunan nasional yang adil dan inklusif.
Refleksi Publik dan Harapan
Momen putusan MK harus menjadi refleksi bersama: zakat bukan sekadar ibadah ritual, melainkan instrumen keadilan sosial. Potensi zakat nasional yang besar tidak boleh berhenti sebagai angka penghimpunan, tetapi harus dikelola secara transparan dan berpihak pada mustahik.
Dukungan publik terhadap JR menjadi penting. Masyarakat sipil perlu menyuarakan harapan agar MK memutus dengan adil dan progresif. Dukungan ini sekaligus memberi pesan bahwa publik siap mengawal reformasi zakat demi kepentingan umat, bukan lembaga tertentu.
Pemerintah juga harus menyadari, apapun putusan MK nanti, reformasi tata kelola zakat tidak bisa ditunda. Putusan MK seyogianya dijadikan momentum untuk membuka dialog dengan masyarakat, memperkuat peran LAZ, dan membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan publik.
Harapan pada Mahkamah Konstitusi
MK memegang peran historis dalam perkara ini. Putusan progresif akan menegaskan keberpihakan MK pada rakyat, melindungi hak konstitusional, dan membuka jalan bagi tata kelola zakat yang adil. Sebaliknya, jika MK tetap membiarkan dominasi kelembagaan yang ada, maka kesempatan emas menata ulang zakat nasional akan terbuang.
Publik berharap MK tidak hanya melihat perkara ini sebagai isu formal hukum, tetapi sebagai bagian dari proses demokratisasi filantropi Islam. Putusan yang visioner akan menjadi katalis bagi pemerintah untuk meneguhkan agenda RPJMN dan Inpres, sekaligus mengembalikan zakat ke ruh aslinya: instrumen kesejahteraan yang lahir dari umat untuk umat.
Menanti Putusan MK
Menanti putusan MK atas JR UU Zakat berarti menanti arah baru pengelolaan dana umat. Publik berhak berharap zakat tidak lagi dikuasai segelintir institusi, tetapi dikembalikan sebagai hak umat. Momentum ini juga kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen pada reformasi tata kelola sesuai RPJMN 2025–2029 dan Inpres 8/2025.
Kini, bola ada di tangan MK. Publik menanti, apakah zakat akan kembali ke pangkuan umat dengan tata kelola yang transparan dan partisipatif, atau tetap terjebak dalam sentralisasi yang menutup ruang partisipasi.[R5]