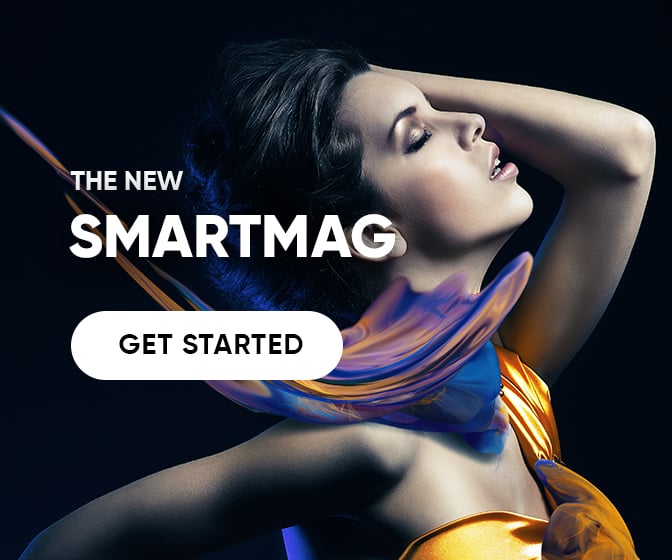Ketika tanggal 17 Agustus datang, masyarakat Indonesia ramai-ramai mengibarkan bendera, mengenakan pakaian adat, mengikuti lomba-lomba, dan bernyanyi penuh semangat tentang kemerdekaan. Tapi di tengah gegap gempita perayaan itu, seorang perempuan justru memilih diam sejenak untuk bertanya: apakah kita benar-benar sudah merdeka?
Dia adalah Devi Virhana, perempuan asal Sumatera Barat yang dikenal sebagai pegiat bahasa Indonesia untuk penutur asing, penulis, dan pembuat konten motivasi. Uniknya, Devi tidak berasal dari latar belakang pendidikan atau sastra. Ia lulusan Ilmu Komunikasi, namun justru menaruh cinta yang dalam terhadap bahasa, sastra, seni, dan pendidikan.
Cinta itu ia wujudkan melalui tindakan nyata: mengajar bahasa Indonesia secara sukarela kepada penutur asing dari lebih dari 15 negara, membina lebih dari 170 siswa asing melalui wadah belajar BIPA Pertiwi yang dimulainya sejak 2021, serta mengembangkan minat dan bakat mereka dalam bidang presentasi, membaca pantun, bercerita, hingga berpuisi. Berkat pembinaan yang konsisten dan penuh dedikasi, banyak dari siswa-siswanya berhasil meraih penghargaan tingkat internasional dalam ajang berbahasa Indonesia.
Namun di balik kiprahnya sebagai penggerak cinta bahasa, Devi juga menyimpan kegelisahan mendalam terhadap kondisi negeri. Baginya, kemerdekaan bukan sekadar perayaan, melainkan pekerjaan rumah yang belum selesai. Karena itu, pada momen 17 Agustus 2025, ia menulis sebuah puisi berjudul “Kemerdekaan yang Tertawan” sebuah karya yang menjadi cermin dan tamparan lembut bagi kita semua.
Makna di Balik Puisi yang Berjudul “Kemerdekaan yang Tertawan”
Puisi ini adalah refleksi tajam tentang kemerdekaan yang masih bersifat semu. Devi membuka puisinya dengan menggugah kembali memori perjuangan para pahlawan darah, bambu runcing, sumpah pemuda sebagai simbol bahwa kemerdekaan kita bukanlah hadiah, tetapi hasil tetesan darah dan air mata.
Namun setelah mengingatkan tentang harga mahal kemerdekaan, Devi mengajak kita memandang realitas hari ini, yang baginya menyedihkan: korupsi, kolusi, nepotisme masih merajalela. Keadilan bisa dibeli, jabatan bisa diwariskan seperti harta, dan suara rakyat seringkali dikalahkan oleh uang dan kekuasaan. Ini adalah bentuk penjajahan baru tanpa seragam perang, tapi lebih mematikan dari dalam.
Tak hanya itu, ia juga menyentil penjajahan terhadap bahasa Indonesia. Kata-kata asing kini memenuhi ruang publik dan ruang pribadi kita: meeting, deadline, deal, hectic nih! seolah lebih bergengsi dibandingkan padanan kata bahasa Indonesia. Devi menggambarkan bahasa ibu seakan menjadi tamu di rumah sendiri, terpinggirkan dan terluka.
Namun puisi ini tidak berhenti pada kritik. Ia mengajak kita untuk bangkit dengan kejujuran, cinta pada bahasa, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Ia menyerukan agar kemerdekaan tidak berhenti sebagai kenangan, tapi dilanjutkan sebagai perjuangan.
Dan seperti seorang pendidik sejati, Devi menutup puisinya dengan harapan: agar anak-anak bangsa tumbuh tidak mudah dibeli, dan kemerdekaan tidak lagi hanya milik masa lalu, tapi benar-benar hidup dalam hati, bahasa, dan negara.
Berikut puisi lengkap karya Devi Virhana:
Kemerdekaan yang Tertawan
Oleh Devi Virhana
Di tanah ini, darah pernah menjadi tinta,
pena dicabut dari ujung bayonet merdeka,
seribu jiwa jatuh tak sia-sia,
demi merah putih yang tak sekadar warna.
Bambu runcing melawan peluru,
sumpah pemuda menembus waktu,
Gelora lisan bersatu dalam satu kata:
“Indonesia”!
Namun kini, setelah bendera tak lagi berlubang,
setelah penjajah asing tak tampak terang,
kita dijajah tanpa seragam perang:
oleh korupsi yang menghisap akar kejujuran,
oleh kolusi yang merayap di dinding-dinding birokrasi,
oleh nepotisme yang menukar otak dengan nama belakang dan memerkosa konstitusi.
Bahasa pun kini tak berkaki di bumi sendiri,
Ia dijajah komplotan kosakata asing yang muncul di setiap lini
“meeting”, “deadline”, “deal”, hectic nih! menjadi puan-puan negeri ini,
sementara ibu bahasa terjepit di sudut hati,
menangis lirih dalam ruang kelas yang sunyi
Wahai para pewaris darah juang,
kemerdekaan bukan hanya soal bendera dikibarkan,
tapi bagaimana rakyat tak lagi dipermainkan,
dan bahasa bersinar di atas panggung peradaban.
Bangkitlah, dengan pena yang jujur dan tangan yang bersih,
hapus luka negeri dengan langkah yang pasti,
Kendalikan navigasi lisanmu untuk lebih mencintai bahasa sendiri,
Tumbuhkan anak-anak yang tak mudah dibeli.
Karena negeri ini belum selesai diperjuangkan,
selama keadilan masih bisa ditawar di pasar belakang,
selama suara rakyat diredam uang dan kekuasaan,
selama kita diam, kita ikut menyekap kemerdekaan.
Mari, menjadi pelanjut nyala juang,
bukan hanya mengenang tapi membangun terang.
Karena sekali merdeka, seharusnya selamanya merdeka
dalam hati, bahasa, dan negara.
Rawamangun, 17 Agustus 2025
Puisi ini adalah panggilan untuk kita semua bahwa perjuangan belum selesai, bahwa mencintai Indonesia bukan hanya dengan mengibarkan bendera, tetapi juga dengan menjaga kejujuran, merawat bahasa, dan melawan ketidakadilan.
Lewat karya dan dedikasinya, Devi Virhana mengingatkan kita bahwa kemerdekaan sejati bukanlah seremoni tahunan, tapi komitmen harian untuk terus berani berkata, berkarya, dan mencintai Indonesia dalam makna yang sesungguhnya.[]